KOMUNIKASI MASYARAKAT MADURA
“BLATER”
DIAJUKAN
OLEH:
UJANG SAIFULLOH
Ujang Saifulloh
140531100100
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
BANGKALAN
2017
Didalam masyarakat Madura, Kekerasan
dan religiusitas adalah dua hal yang melekat. Padahal keduanya sangat paradoks.
Atau dengan kata lain mengandung makna yg berseberangan. Orang yg religius akan
menolak segala bentuk kekerasan, karena hal tersebut berlawanan dengan ajaran
agama. Sebaliknya, orang yang akrab dengan dunia kekerasan hidupnya jauh dari
nilai-nilai religiusitas. Namun realitas sosial selalu menghadirkan
kompleksitas masalah yang tidak selalu merujuk pada normatifitas teori yang
bersifat literal. Kekerasan dan religiusitas dalam konteks kebudayaan tidaklah
hadir dalam ruang hampa. Eksistensinya selalu beririsan dengan relasi kuasa dan
kepentingan antar aktor di dalam struktur sosial masyarakat.
Bila melihat dari konteks dan motifnya,
kekerasan cenderung beragam. Misalnya, tradisi carok di dalam masyarakat Madura
sebagai upaya penyelesaian konflik dengan kekerasan. Orang Madura akan
melakukan carok bila harga diri dan kehormatannya merasa terusik, diganggu atau
dilukai. Jadi dalam peristiwa carok motif dan sasarannya sangat jelas, yakni
individu yang sedang saling berselisih paham yang sulit didamaikan karena sudah
menyangkut harga diri yang terluka. Orang Madura yang melakukan tindakan
kekerasan, dalam bentuk carok untuk membela harga diri dan kehormatan, baik
kerena dipicu oleh kasus-kasus di atas atau yang sejenisnya akan dinilai, dan
dipandang memiliki keberanian sebagai seorang blater. Orang Madura yang
mengambil jalan ‘toleran’, bukan tindakan carok ketika dihadapkan dengan
kasus-kasus pembelaan harga diri seperti di atas akan dipandang oleh masyarakat
Madura sebagai orang atau keluarga yang tidak memiliki jiwa keblateran.
Blater sendiri dalam banyak hal
seringkali merujuk pada sosok jagoan sebagai orang kuat di masyarakat pedesaan.
Tak heran bila konstruksi tentang keblateran sangat terkait pula dengan
konstruksi jagoanisme di dalam masyarakat. Seperti cerita Sakera yang begitu
melegenda di kalangan warga Madura. Sakera adalah jagoan keturunan Madura yang
melakukan perlawanan terhadap Belanda di daerah Pasuruan. Daerah yang disebut
dengan nama tapal kuda, berlokasi di bagian pulau Jawa di bagian timur yang
penduduknya multi etnik, namun sebagian besar keturunan Madura. Kebanyakan di
daerah tapal kuda ini, seperti Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo dan
Banyuwangi, bahasa Madura dipergunakan secara populer sebagai bagian dari
bahasa keseharian, disamping juga bahasa Jawa. Cerita tentang jagoan keturunan
Madura ini terjadi di daerah Pasuruan. Sakera adalah sosok blater atau jagoan yang
tidak mau tunduk terhadap penjajah Belanda. Sakera memiliki ilmu bela diri dan
ilmu kebal. Peluru pasukan Belanda tidak mampu menempus tubuh Sakera dalam
suatu pertempuran. Berkali-kali pasukan Belanda berupaya menumpas perlawanan
Sakera, dan selalu gagal. Sampai akhirnya Belanda mengetahui kelemahan kekuatan
ilmu kebal Sakera. Sakera di jebak oleh Belanda dalam suatu kegiatan kesenian
rakyat yang bernama sandur. Sakera diperbolehkan menari, dengan syarata melepas
seluruh jimat yang dimilikinya. Usai jimat dilepas, dalam suasana ia sedang
menari dengan perempuan pasukan Belanda menyergapnya dan peluru pun ditembakkan
ke tubuhnya. Sakera terkapar dan meninggal saat itu juga. Cerita ini menjadi
legenda hidup di kalangan masyarakat Madura hingga saat ini. Masyarakat Madura
sangat senang dan bangga bila mendengar atau diceritakan ulang berkenaan dengan
kisah Sakera ini. Ada rasa kebanggaan atas sosok keblateran dan jiwa
kepahlawanannya. Meskipun cerita itu mengandung bahu kekerasan akan makna
perlawanan.
Blater adalah sosok orang kuat di
Madura, baik secara fisik maupun magis dan biasanya dikenal memiliki ilmu
kebal, pencak silat atau ilmu bela diri. Seorang jago/blater dapat dengan mudah
mengumpulkan pengikut, anak buah dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun
besaran jumlah pengikutnya sangat tergantung atas kedigdayaan ilmu (kekerasan)
yang dikuasainya. Sosok jago atau blater yang sudah malang melintang di dunia
kekerasan, dan namanya sudah sangat tersohor karena ilmu kesaktianya akan
menambah kharisma dan kekuatannya untuk mempengaruhi banyak orang.
Bila dilihat dari asal usul
sosial dengan mengacu pada sistem ekologis Madura, kemunculan komunitas
blater terkait pula dengan ekosistem tegalan dengan area tanah pertanian yang
tandus, gersang dan tidak produktif bagi sistem pertanian sawah. Kondisi ini
diperparah pula oleh adanya curah hujan yang sangat terbatas membuat para
petani Madura menghasilkan produk pertanian yang serba terbatas. Kondisi ini
secara langsung menciptakan kondisi kemelaratan dan kemiskinan di kalangan
warga desa. Lahan pertanian yang tidak memberikan keuntungan ekonomis disertai
peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari tahun ke tahun menciptakan
problem ekonomis yang cukup akut. Kondisi ini tak jarang membuat orang Madura
mengambil pilihan untuk migrasi sebagai solusi yang dianggap strategis guna
memperbaiki masa depannya. Sekalipun pada kenyataannya migrasi bukan pula jalan
satu-satunya dalam perbaikan nasib atau cara untuk dapat bertahan hidup. Cara
lain yang oleh sebagian anggota masyarakat dipandang sebagai cara atau jalan
“hitam” adalah dengan menjadi bandit atau blater.
Perilaku perbanditan, disertai
dengan kekerasan bahkan pembunuhan, pencurian, perampokan dan pembakaran di
Madura mulai marak saat kekuasaan kolonialisme Belanda merambah kawasan ini.
Negara kolonial tentu sangat risau dengan perangai dan perilaku orang Madura
ini karena dapat menguncang stabilitas keamanan dan perdagangan. Guna mengatasi
perbanditan di pedesaan ini, Belanda jarang sekali menggunakan pendekatan
hukum–proses pengadilan—tetapi yang paling dominan yang dilakukan di Madura
adalah dengan cara kekerasan dan pola berkolaborasi terselubung dengan
para bandit itu sendiri. Menangkap bandit dengan bandit, begitulah cara yang
paling sering digunakan. Selain cara ini dianggap lebih efisien juga karena
negara kolonial tidak cukup mampu menkooptasi seluruh kekuatan masyarakat
sampai ke akar-akarnya di pedesaan. Pola dan cara itu dianggap efektif
dilakukan, disebabkan pula tidak adanya niatan dari pihak kolonialis untuk
membangun institusionalisasi negara yang berorientasi pada stabilisasi keamanan
untuk kemakmuran masyarakat lokal. Dalam konteks ini, kekuasaan kolonialis juga
ditegakkan melalui jasa para bandit, blater sebagai sosok jagoan desa.
Banyak kasus menunjukkan di dalam
masyarakat, yakni seseorang yang sebelumnya dipandang bukan sebagai golongan
blater, disebut sebagai blater oleh warga lainnya karena berani melakukan
carok. Apalagi menang dalam adu kekerasan carok itu. Jadi penyebutan masyarakat
atas sosok blater dalam hal ini sangat erat kaitanya dengan keberanian
melakukan carok dalam menghadapi konflik dan permasalahan di dalam lingkungan
masyarakat. Di sini carok dijadikan sebagai arena legitimasi untuk mengukuhkan
status sosial seseorang sebagai seorang blater. Jadi identitas keblateran dapat
merujuk pada sifat pemberani, angkuh dan punya nyali menempuh jalur kekerasan
dalam penyelesaian konflik harga diri. Meskipun carok bukanlah satu-satunya
arena untuk melegitimasi status seseorang menjadi blater.
Dinamika yang berlangsung
menciptakan kultur dan komunitas tersendiri di dalam masyarakat Madura. Tak
heran bila seseorang sudah memiliki identitas dan status sosial sebagai seorang
blater eksistensinya memiliki posisi sosial tertentu di dalam masyarakat
Madura. Sosok blater selalu disegani dan dihormati secara sosial. Sangat jarang
sekali ditemukan seseorang yang sudah dikategorikan sebagai blater dipandang
rendah secara sosial.
Dari sudut pandang sosial, blater
dapat muncul dari strata dan kelompok sosial manapun di dalam masyarakat
Madura. Baik itu di dalam lingkungan dengan latar belakang sosial keagamaan
yang ketat, seperti santri misalnya, atau dari lingkungan sosial blater sendiri.
Bagi masyarakat Madura sendiri bukanlah sesuatu yang aneh bila seorang blater
pandai mengaji dan membaca kitab kuning karena dalam tradisi masyarakat Madura,
pendidikan agama diajarkan secara kuat melalui suarau, masjid, atau lembaga
pesantren yang bertebaran di hampir setiap kampung dan desa. Konteks ini pula
yang membuat blater dengan latar belakang santri memiliki jaringan kultural dan
tradisi menghormati sosok kiai.
Peran agama, dalam hal ini islam, begitu
sentral dalam dinamika kehidupan masyarakat Madura. Berbagai ritus sosial
selalu dikaitkan dengan spirit keagamaan dengan kiai sebagai aktor utama.
Dinamika sosial tersebut membuat agama memiliki akar dalam struktur sosial dan
kultural masyarakat sehingga mengalami proses penyatuan identitas. Dalam proses
inilah agama islam menjadi bagian dari martabat dan harga diri orang Madura.
Ketika agama sudah menjadi bagian dari harga diri dan martabat itulah maka
adanya gangguan atau sesuatu yang berbau melecehkan agama, disepandankan dengan
melecehkan harga diri dan identitas kemaduraan. Dengan demikian, adanya
gangguan atau pelecehan atas nama agama dapat menimbulkan resistensi. Proses
kultural ini dipersepsikan sebagai bentuk dari religiusitas kemaduraan.
Dinamika kultur kekerasan dan
religiusitas di dalam masyarakat Madura sama-sama memiliki aktor utama, yakni
blater dan kiai. Keduanya dapat dipandang sebagai rezim kembar yang memiliki
kekuatan dalam mereproduksi wacana, kultur, tradisi dan jejaring kuasa di
tengah masyarakat. Blater dengan legitimasinya sebagai pengendali dan pengelola
mesin-mesin kekerasan kerapkali menghegemoni masyarakat. Begitu pula dengan
kiai, dengan kapasitas dan kemampuannya dalam menafsirkan wacana agama mampu
menghegemoni struktur terdalam di ruang batin, pikiran dan perilaku masyarakat.
Media-media keagamaan yang bertebaran di Madura dengan sendirinya membuat kiai
semakin signifikan dalam dinamika masyarakat Madura. Kedua aktor ini dalam
praktek sosialnya, terkadang saling berseberangan paham dan visi. Namun dalam
konteks tertentu tak jarang pula saling menjalin relasi kultural, ekonomi dan
politik kuasa..
Bertemunya realitas sosio-kultural
masyarakat dengan struktur kekuasaan negara yang saling mengakomodasi
unsur-unsur premanisme membuat entitas blater memiliki elasitas,
kelenturan sehingga dapat hadir di berbagai posisi kultural dan struktural. Pengalaman
di masa Orde Baru ketika praktek banditisme begitu marak di Madura pada tahun
1980, pemerintah pusat mengelar operasi bagi kaum blater atau bajingan yang
dikenal dengan sebutan petrus (penembak misterius). Operasi petrus ini
merupakan kebijakan pemerintah Soeharto yang begitu resah dengan makin
meningkatnya kriminalitas di Ibu kota dan kota-kota besar, termasuk di tingkat
pedesaan. Guna mengurangi kejahatan sosial di tanah air. Di kabupaten
Bangkalan, tokoh blater juga menjadi sasaran petrus. Namun demikian, bukan
berarti kebijakan petrus ini dengan sendirinya membuat kekuasaan negara ini
membersihkan secara total para aktor perbanditan dan jaringan kriminalitas di
tengah masyarakat, sebab tidak lama setelah itu, khususnya ketika kekuasaan lagi-lagi
membutuhkan keterlibatan blater, preman untuk pemeliharaan kekuasaannnya,
elemen blater digunakan kembali sebagai mitra. Terutama setiap menjelang
pemilu, di saat rezim Orde Baru ingin memperbaharui legitimasi
kekuasaannya.
Jaringan kerjasama terselubung
antara blater dengan aparat keamanan sudah menjadi pemandangan umum di Madura.
Jalinan ini terbentuk karena terdapat proses yang saling memberikan keuntungan
bagi keduanya, baik secara politik dan ekonomi. Pemerintah dapat meminjam
‘tangan’ blater untuk merepresi warga untuk mendukung partai pemerintah tanpa
perlu susah payah. Bagi blater sendiri koneksi dengan pemerintah membuatnya
merasa terlindungi dari mesin-mesin hukum, terutama dalam hal menjalankan
bagian dari profesinya yang bersentuhan dengan aksi kriminalitas. Pola hubungan
blater dengan aparat kepolisian, khususnya tidak hanya berlangsung pada saat
pemilu semata. Hubungan itu berlanjut pasca pemilu terkait dengan transaksi
ekonomi politik kasus-kasus kriminalitas. Misalnya adanya peranan blater
sebagai broker kasus melalui praktek suap bila seseorang ingin bebas dari jerat
hukum ketika melakukan carok atau kasus kriminalitas lainnya. Pola kerjasama
demikian bahkan di era Reformasi pun masih berlangsung, meskipun secara
terselubung.
Era Reformasi makin menunjukkan
perluasan arena politik blater, dari ranah kultural ke struktural. Dari
tingkatan politik pedesaan pada politik perkotaan. Peristiwa politik di
Kabupaten Bangkalan makin menegaskan akan hal itu. Setelah sebelum ini jabatan
bupati selalu dikuasai oleh kalangan tentara atau lingkungan birokrasi maka
pasca Reformasi figur blater dapat mengambil alih kekuasaan lokal itu. Figur
atau sosok Fuad memang berasal dari lingkungan keluarga santri. Kakeknya adalah
kiai terpandang di Bangkalan bahkan Madura, dan keluarganya banyak yang
mendirikan pesantren serta memiliki pengaruh di masyarakat, parpol dan
birokrasi pemerintahan. Namun secara sosial ia dibesarkan di dalam tradisi dan
komunitas blater. Posisi ini membuatnya memiliki pengaruh di dua komunitas,
blater dan kiai. Ketika Fuad terpilih sebagai bupati melalui pemilihan di
tingkat parlemen lokal, warga masyarakat menyebutnya sebagai kiai blater
terpilih sebagai bupati.
Dalam kasus pemilihan bupati secara
langsung oleh rakyat di kabupaten Sumenep dimenangkan oleh Ramdan Siraj, yang
berasal dari asal usul sosial dari lingkungan kiai. Keberhasilannya dalam
kompetisi Pilihan Bupati (Pilbub) adanya dukungan blater juga tidak dapat
dinafikan. Di Sumenep sebagian besar para kepala desa atau Klebun juga
memiliki kultur blater. Posisi sebagai klebun sangat strategis di masyarakat
karena dianggap figur yang dituakan, selain kiai. Di daerah Sumenep, para
blater—mereka lebih menyebutnya sebagai kelompok bajingan— membuat perkumpulan
yang diberi nama ‘Selendang Hitam’. Nama perkumpulan ini dipakai karena umumnya
mereka menggunakan fashion selendang atau ikat kepala
atau odeng dalam bahasa Maduranya. Sedangkan kata hitam
merujuk pada perilaku atau profesinya yang dianggap berdekatan dengan dunia
kriminalitas.
Pola perkembangan blater atau bajingan berjaringan melalui
organisasi atau perkumpulan makin menandai betapa strategisnya peran politik
blater di era Reformasi. Bila mengamati kehidupan ekonomi politik komunitas
blater sebelum Reformasi umumnya berada di sekitar sektor informal. Profesi
ekonomi yang digelutinya adalah menjalani praktek bisnis uang bunga (rentenir),
jasa keamanan dan kekerasan, pencurian, perjudian. Ada pula yang berprofesi
sebagai pedagang yang baik, bukannya dengan jalan banditisme, semisal dengan
menjalani perdagangan produk lokal, seperti jual beli ternak sapi, perkayuan
dan sejenisnya. Kalau toh mereka berkiprah di panggung politik formal, hanya
sebatas menduduki jabatan sebagai kepala desa, istilah Maduranya klebun.
Desa-desa di Madura kebanyakan dikuasai oleh para blater. Penguasaan atas
politik lokal desa menunjukkan bahwasannya blater memiliki akar sosial dan
jaringan serta pengaruh di kalangan warga. Dalam konteks rezim otoritarian Orde
Baru memang sulit bagi jaringan blater ini berkembang pada tingkatan yang lebih
tinggi, seperti politik-kuasa di tingkat kabupaten. Namun era Reformasi, dimana
keterbukaan dan kompetisi politik relatif lebih menjamin bagi mereka yang
memiliki dukungan di tingkatan warga masyarakat, politik blater memungkinkan
untuk berkembang ke politik formal pada tingkatan kabupaten bahkan sampai
tingkat yang lebih puncak lagi.
Dinamika politik di tingkat desa dan
juga di tingkat kabupaten, energinya berada di tangan dua komunitas, yakni
blater dan kiai. Kalau kedua komunitas ini memiliki concern terhadap
perbaikan kualitas layanan publik masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan,
perumahan dan lainnya dalam tata kuasa pemerintahan maka pelaksanaan otonomi
dan desentralisasi politik di Madura akan mendulang masa depan yang
mengembirakan. Namun, bila kedua komunitas ini tidak memiliki concern atas
perubahan dan perbaikan maka masyarakat Madura akan menghadapi masa-masa suram,
justru di tengah era desentralisasi yang menjadi dambaan banyak pihak yang
begitu lelah dengan sentralisasi di era Orde Baru. Memang ada komunitas lain di
luar kedua maisntreams itu, yakni kalangan akademisi. Namun perannya masih
belum signifikan dalam mempengaruhi politik kuasa di Madura.
Lihat juga:
Lihat juga:
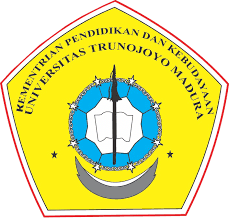
Tidak ada komentar:
Posting Komentar